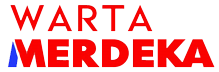Jika kita bicara mengenai politik nasional pada hakikatnya kita membicarakan tujuan-tujuan dari kebijakan yang orietasinya kepada kepentingan rakyat secara kolektif di bumi nusantara. Oleh karena itu, di dalam tulisan kali ini,saya tidak akan membicarakan politik nasional ini lepas dari tujuan-tujuan sosial yang tertanam di dalam gerak maju revolusi Indonesia. Saya tidak mengatakan bahwa berbagai wacana dan program yang ditawarkan pemerintah yang telah kita alamisejak kemerdekaan Republik Indonesia mempuyai visi politik kebudayaan. Tapi kita bisa mengatakan secara sadar keaktifan-keaktifan dan pemikiran-pemikiran yang bersama-sama dirumuskan dan memberi arah kepada kehidupan dan kebudayaan Indonesia sejak proklamasi, berkisar di sekitar dua masalah pokok, yaitu masalah peraturan nasional dan masalah modernisasi; terhadap kebudayaan-kebudayaan Indonesia yang dianggab pramodern, tradisioanal, dan dianggap perlu di sesuaikan atau menyesuaikan diri pada tuntutan-tuntutan zaman dan kepada tanggung jawab baru yang menjadi konsekuensi dari kemerdekaan bangsa.
Rebutan Kursi Bukan Sembarang Kursi
Saat ini, banyak orang berebut kursi. Bukan sembarang kursi, tetapi kursi yang menarik bagi semua orang. Mereka yang duduk di tempat itu, suaranya didengarkan, perintahnya diikuti, keputusannya dijadikan pedoman, berprestise dan tentu saja siapa yang duduk di kursi itu akan mendapatkan sesuatu yang selalu di cari oleh banyak orang. Kursi yang dimaksudkan itu tidak lain dan tidak bukan adalah kursi keskuasaan.
Dulu di zaman kerajaan, kekuasaan tidak diburu, tetapi cukup ditunggu,. Siapa pun putra Raja yang menadapatkan warisan kekuasaan. Anak seorang Raja, tatkalah orang tuanya sudah mangkat, maka salah seorang akan mewarisinya. Sedangkan anak yang lain, diberi posisi penting lainnya. Lewat sistem itu, mereka yang bukan tergolong anak Raja, misalnya hanya sekedar anak petani, pedagang di pasar, nelayan yang penghasilannya tidak menentu, apalagi pengangguran, sekalipun berpendidikan, tidak akan mungkin meraih derajat itu.atii
Berbeda dengan zaman feodal adalah saat orang percaya pada sistem demokrasi seperti akhir-akhir ini. Siapapun bisa menjadi bupati, walikota, gubernur, anggato DPRD, DPR, dan bahkan Presiden. Semua jabatan yang harus diperoleh lewat pemilihan, dengan melibatkan rakyat, maka siapapun berpeluang untuk meraihnya. Siapapun orangnya boleh mencalonkan diri asal mau, memnuhi syarat, berani, dan merasa mampuh.
Orang yang semula aktif sebagai pedagang, pengusaha, tentara, pejabat politik, PNS, bahkan pengangguran sekalipun, asal yang bersangkutan dikenal atau mampuh mengenalkan diri kepada masyarakat dan memenuhi syarat-syarat yang sebenarnya tidak terlalu sulit dipenuhi, maka boleh ikut berkompetensi memperebutkan kursi kekuasaan itu, karena itu, akhir-akhir ini ada saja orang yang semula bekerja sebagai pedagang, petani, dokter, kepala sekolah, guru, juga kiayi terpilih menjadi pejabat politik.
Lewat demokrasi, posisi atau peran seseorang bisa berubah dengan cepat seseorang yang semula di kenal sebagai pengusaha berali menjadi aktivis politik, dan akhirnya menjadi bupati, walikota, anggota DPRD, Gubernur, dan juga yang mencalonkan diri menjadi presiden. Pejabat politik akhirnya tidak di monopoli oleh keluarga tertentu, kelompok tertentu, aliran tertentu, dan juga latar belakang sosial tertentu. Inilah buah demokrasi.
Namun hal yang perlu disadari adalah bahwa apapun tidak terkecuali berdemokrasi yang sedang berjalan saat ini, juga ada resiko. Keterbukaan ini membawah konsekuensi yang kadang juga tidak sederhana. Seseorang yang terlalu bersemangat, percaya diri, tidak memiliki kemampuan dalam melakukan kalkulasi politik, kemudian ikut mencalonkan diri sebagai pejabat politik dan gagal, maka akan kalah segalah-galahnya. Mereka gagal menjadi pejabat politik dan masih di tamba lagi, kekayaan yang bertahun-tahun dikumpulkan hilang seketika untuk membiayai pencalolanannya itu. Resiko juga kadang menimpah mereka yang sukses. Seseorang menjadi pejabat politik melakukan korupsi, akhirnya tertangkap KPK dan kemudian di penjarahkan.
Kerugian di alami oleh rakyat, mereka diberi janji-janji indah yang kadang berlebihan. Seseorang yang sebenarnya belum banyak berbuat untuk rakyat, sehingga belum dikenal secara luas, tetapi ingin menjadi pejabat politik. Agar terpilih, mereka mengiklankan diri. Foto-foto besar para calon pejabat politik dengan berbagai ukuran di pasang di tempat-tempat strategis hingga menggangu pemandangan.
Tidak sekedar itu, rakyat juga mendapatkan pelajaran bahwa jabatan ternyata bukan pengabdian, melainkan media untuk mendapatkan keuntungan. Pesta demokrasi dimaknai sebagaimana pesta pada umumnya. Siapapun yang terlibat pesta juga harus mendapat sesuatu. Maka muncullah pameo, siapa yang berani membayar mahal, merekalah yang akan dipilih.
Cara berpikir demikian itu menjadikan demokrasi salah arah. Rakyat digiring tidak memilih calon pemimpin kompeten, berpengalaman, mampuh memimpin dan menyejahterakan rakyat, melainkan sekedar diajak untuk mengikuti siapa yang memberi sesuatu paling menguntungkan. Terjadilah praktek-praktek jual beli suara, money politik, suasana serba transaksionaal, dan efek negatif lainnya. Berbagai bentrok terkait dengan pilkada terjadi dibeberapa tempat dan kasus-kasus korupsi sebenarnya berawal dari praktek-praktek demokrasi yang tidak pada tempatnya itu.
Pemilihan pejabat politik yang berbiaya tinggi seperti itu ternyata membuahkan resiko negatif lainnya. Misalnya, partisipasi masyarakat terhadap pembangunan diberbagai level melemah, kehidupan sosial di warnai transaksi untuk memburu keuntungannya sendiri-sendiri, kepercayaan masyarakat melemah, dan bahkan kewibawaan pemerintah terdegradasi. Dulu kewibawaan para pejabat politik atau pemerintah sedemikiaan terasa. Namun pada akhir-akhir ini, taklah banyak orang berebut kursih kekuasaan, maka kewibawaan pejabat politik di hadapan rakyat menjadi semakin hilang.
Karena sudah diperebutkan atau dijual belikan, maka jabatan dan kekuasaan tidak ubahnya barang dagagangan di pasar. Tidak pernah ada kewibawaan di tengah pasar atau di tempat-tempat orang bertransaksi. Sesuatu yang bernilai tinggi di pasar bukan orang, melainkan barang dan uang. Seperti itulah tatkalah kondisi jabatan dan kekuasaan jika sudah dipasarkan dan di perebutkan. Kewibawaan pejabatnya juga semakin runtuh.
Antara Kawan dan Lawan Politik
Banyak orang berkumpul dan menyatu tatkala memiliki kepentingan yang sama. Begitu pula berpisah dianggap menjadi hal biasa tatkala kepentingan itu dirasa sudah tidak ada lagi. Bahkan dalam berpolitik ternyata lebih tragis lagi, kawan bisa saja berubah menjadi musuh dan sebaliknya, musuh bisa menjadi kawan. Dalam berpolitik, ikatan itu hanyalah pada kepentingan belaka.
Sebenarnya, perkawanan dalam partai politik tidak saja diikat oleh kepentingan, tetapi juga oleh ideologi hingga melahirkan sikap militan. Sementara pada saat sekarang ini, banyak kader partai politik yang melakukan penyimpangan hingga harus dikeluarkan dan bahkan dipenjarakan. Itu semua adalah pertanda bahwa partai politik yang bersangkutan itu masih belum berhasil membangun ideologi yang jelas dan kokoh. Mereka masuk menjadi kader partai politik bukan karena panggilan cita-cita perjuangan yang jelas, melainkan hanya atas dasar kepentingan praktis dan pragmmatis belaka.
Dalam suasana budaya transaksional sperti ini, suasana organisasi dan apalagi partai politik akan rentan konflik. Saling berebut adalah menjadi hal biasa. Perebutan itu bukan atas dasar ideologi yang seharusnya diperjuangkan, melainkan didorong oleh keinginan untuk mendapatkan keuntungan praktis. Berawal dari sinilah sebenarnya partai politik menjadi rentan konflik dan menjadi ajang perebutan sesuatu yang sebenarnya di luar kepentingan partai politik. Maka, agar organisasi atau partai berdiri tegak dan kokoh, yang pertama kali harus dilakukan secara terus-menerus adalah meneguhkan cita-cita atau ideologi partai politik yang bersangkutan. Jika hal demikian itu bisa terlaksana, niscaya pertemanan dalam partai politik bisa terus bertahan, dan juga tidak terbatas sebatas kepentingan praktis dan pragmatis belaka. ***